by Azaki Khoirudin
Gerakan Kritis
Transformatif muncul karena keterpakasaan dengan perubahan nama Ikatan
Pelajar Muhammdiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan perubahan
tersebut mau tidak mau paradigma gerakan harus berubah dan mulai masuk keranah sosial. Pada Muktamar XII Jakarta, IRM sudah mengarah ke gerakan sosial (social movement)
kemudian dilanjutkan di Muktamar XIV di Bandarlampung, sampai
mendeklarasikan diri sebagai Gerakan Kritis Transformatif, dengan ciri
gerakan peka, sadar, dan peduli pada problem sosial, aksi nyata untuk
melakukan perubahan, visioner dan memiliki sepirit kepeloporan.
Secara
normatif, praksis gerakan Kritis-Transformatif diharapkan menciptakan
gerakan yang lebih progresif. Akan tetapi secara empiris, gagasan dan
praksis gerakan belum terinternalisasi secara mendalam pada tubuh
gerakan kita. Butuh waktu sepuluh tahun untuk mencari komposisi yang
tepat corak gerakan IRM, ditambah dua tahun untuk memantapkan diri
mengadopsi ramuan Gerakan Kritis Transformatif sebagai paradigma gerakan
IRM. Kenyatannya, sampai sekarang kesadaran Kritis Transformatif belum
terealisasi secara sempurna.
Muktamar XV di medan muncul wacana back to school
dengan kata lain ingin berubah menjadi IPM, walaupun dalam musyawarah
yang berskala nasional ini belum bisa merubah IRM menjadi IPM tetapi
terbentuk tim eksistensi yang tugasnya mengkaji perubahan nama tersebut.
Akhirnya pada Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 di Jogja, keluarlah Surat
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammaadiyah No. 60/KEP/I.0/B/2007 tentang
perubahan nomenklatur Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar
Muhammadiyah. Lagi –lagi paksaan itu yang tergambar perihal keluarnya SK
PP Muhammadiyah tersebut. Dengan berbagai macam gejolak pro dan kontra,
pada Muktamar XVI di Surakarta IRM resmi menjadi Ikatan Pelajar
Muhammadiyah. Pertanyaannya sekarang adalah Apakah kita akan mencari
selama sepuluh tahun lagi untuk menentukan paradigma gerakan IPM ?,
Apakah masih relevan Gerakan Kritis Transformatif di pakai di IPM dalam
konteks saat ini?
Mengkaji Relevansi Paradigma Kritis dengan IPM
Tanfids hasil Muktamar di Medan dan Musywil IRM Jawa Tengah di Pekalongan menerangkan bahwa basis masa IRM adalah remaja dan pelajar. Sehingga, secara tidak langsung arah kebijakan IRM menjurus pada problematika Pelajar yang notabene remaja. Hal ini dibuktikan dengan agenda aksi IRM yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan pelajar, misalnya: gerakan iqro’, jurnalis sekolah / jurnalistik untuk pelajar dan genda aksi lain yang memuat nilai kritis transformatif. Artinya bahwa fondasi menuju gerakan pelajar dengan konteks saat ini telah dibangun. Dan perubahan IRM – IPM memang sudah seharusnya karena sebenarnya memang sudah siap. Namun yang perlu dikaji setelah berubah nama kembali memakai IPM pada Muktamar XVI IRM di Solo yang mengsusng Gerakan Pelajar baru dan pada Muktamar XVII di Bantul Yogyakarta IPM dengan tegas mendeklarasikan dirinya dengan nama Gerakan Pelajar Kreatif. Dengan alasan Gerakan Kritis Transformatif kurang aplikatif sehingga diciptakannya Gerakan yang lebih aplikabel.
IPM adalah sebuah organisasi hidup yang dinamis. Cirinya adalah bergerak seirama sejalan ketika melihat kemungkaran (dehumanisasi) ditegakkan dan selalu gelisah melihat fenomena westernaisasi, kapitalisme, globalisme, hedonisme, dan sebagainya. Benarkah nilai-nilai positif itu masih bisa diklaim oleh kader-kader atau simpatisan IPM? Bisakah pasukan elite IPM di level pusat dan wilayah berfikir apa yang sedang terjadi setelah hampir separuh abad gerakan ini dilahirkan? Bisakah kita berfikir, refleksi kritis dan ideologis tentu akan memberikan bobot tersendiri bagi keberlangsungan kader dan pergerakan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bangsa ini masih butuh sumbangsih gerakan pelajar tetapi gerakan pelajar yang bagaimana yang memberikan ruang yang kondusif untuk perubahan pelajar Indonesia. Disinilah pentingnya kita berpikir keras tentang paradigma yang digunakan oleh IPM di era ini.
Salah satu ancaman tersendiri adalah muncul dari dalam IPM, yaitu kita IPM sudah memiliki paradigma yang dibangun kesadaran kritis. Tetapi akan sulit apabila kita selalu menggunakan kesadaran naïf dimana semua persoalan pelajar ditambatkan pada kapasitas individu pelajar daripada mempersoalkan struktur. IPM sendiri, tidak bisa lepas sebagai penyandang dua status dalam waktu relative bersamaan yaitu: as part of problems and as part of solution (bagian dari masalah dan bagian dari solusi). Karena inilah kelemahan dipertanyakan berulang-ulang. Disisi lain IPM ingin menjadikan dirinya sebagai problem solver (rahmatan lilalamin) ditengah berbagai persoalan pelajar, namun paradigma yang digunakan belum menjadi seorang Dokter Persoalan Pelajar, yaitu masih melihat dirinya sebagai bagian masalah.
Disisi lain, Gerakan kritis transformative yang berparadigma atas kesadaran kritis adalah lintasan jauh ke depan lalu dikerdilkan kembali dengan persoalan militansi, lalu diperkuat dengan kedaulatan pelajar dan dilenyapkan dengan pragmatisme, kini muktamar ke 17 di bantul menunjukkan menguatnya aliran developmentalisme dalam tubuh IPM. Ideologi semakin sirna dengan kemunculan ide Gerakan pelajar kreatif yang dimanifestasikan dengan program community based (komunitas sebagai basis gerakan) tanpa bobot ideology dan miskin kerangka rekayasa social (social engineering). Apakah paradigma kritis produk GKT ini masih relevan menjadi alat IPM dalam melihat berbagai persoalan pelajar?
Paradigma kritis masih relevan dikembangkan dalam kondisi sekarang ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma kritis adalah sadar, peka, peduli dan berpartisipasi aktif sebagai subyek. Problematika pelajar yang terjadi saat ini diantaranya, kekerasan terhadap sesama pelajar, peredaran video porno di klangan pelajar, candu dan masih banyak lagi. Ini adalah cara pandang yang masih naïf ketika pelajar yang bermasalah dijadikan sebagai sebab masalah. Kita perlu melihat factor dibalik penyebab yang menjadikan pelajar berbuat demikian. Maka paradigma kritis perlu dipahami dan diertajam lagi dalam aktor elite IPM. Namun Paradigma kritis yang dipakai belum cukup. Supaya IPM yang ingin menjadi problem solver (dokter permasalahan social pelajar) tidak melihat berbagai persoalan pelajar seperti kacamata kuda yang hanya menyalahkan struktus sebagai penyebab masalah. IPM perlu memiliki paradigma elite (gerakan pilihan alternative) yang memiliki taring untuk berbicara pada problem-problem pelajar. Kemudian bagaimanakah paradigma IPM yang lebih memiliki taring sebagai alat untuk mendiagnosa problem pelajar masa kini?
Reinvensi Paradigma Gerakan
Konsep Gerakan Kritis Transformatif terkonstruk dari tiga tahapan yakni, paradigma Kritis, kesadaran Kritis, dan Gerakan Kritis (aksi Kritis). Sebuah gerakan harus dibagun dari sebuah paradigma kritis yang kemudian melahirkan kesadaran kritis, ketika kesadaran kritis terbentuk baru melakukan gerakan kritis dalam betuk aksi transformative yang disebut dengan praksisme-kritis. Paradigma Kritis ialah paradigma yang bertujuan melakukan perubahan struktural dan kultural secara mendasar dalam realitas sosial; ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kesadaran-kritis ialah kesadaran yang dapat melihat bahwa struktural dan kultural sebagai sumber masalah dari realitas sosial. Sedangkan, Gerakan-kritis ialah gerakan yang di lakukan secara sadar, peka , peduli, dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan dalam realitas sosial. Adapun aksi-transformatif ialah melakukan perubahan yang sistematis meliputi aspek diri (personal) dan struktur dan sistem sosial yang ada, dilakukan dengan partisipatoris demi kondisi masa depan yang lebih baik. Yangmana Gerakan kritis- transformatif memiliki tiga kesatuan pondasi utama yang menjadi landasan yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan.
Pada Muktamar XVII di Yogyakarta, IPM selalu melakukan analisis dengan segala persoalan yang ada Bukan berarti Gerakan Kritis Transformatif yang telah di deklarasikan sebelumnya sudah tidak relevan lagi dalam menjawab persoalan saat ini, akan tetapi bagaimana Gerakan Kritis Transformatif dapat di implementasikan lebih riil di lapangan, tidak terkesan kaku dan kuno sehingga mudah diterima dikalangan basis massa IPM, yaitu pelajar saat ini. Dimana para pelajar saat ini hidup di tengah gencarnya arus globalisasi dengan segala bentuk kemajuan zaman yang ada, persaingan yang kompetitif dan pemanfaatan teknologi maupun informasi yang serba canggih, menuntut mereka untuk dapat bersaing di zamannya dan selektif dalam melakukan sebuah pilihan hidup mereka sebagai pelajar. Oleh karena itu, pada Muktamar XVII di Yogyakarta kali ini, IPM kembali mendeklarasikan diri sebagai Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) sebagai jawaban terhadap persoalan yang dihadapi saat ini.[1]
Melalui Gerakan Pelajar Kreatif inilah, IPM kembali menguatkan diri dan mensinergikan ketiga dimensi Iman, Ilmu, dan Amal dalam menjalankan gerakan dakwahnya di kalangan pelajar. Bagaimana IPM dapat melakukan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pembelaan sebagai trilogi gerakan IRM yang pernah di deklarasikan kala itu, kemudian menciptakan sebuah karakter pelajar yang tidak hanya memiliki keshalehan ritual semata tanpa memiliki ilmu dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, atau seorang pelajar yang shaleh dan berilmu, akan tetapi tidak mengamalkannya dengan melakukan sebuah perubahan.[2]
Sejalan paradigma kritis IPM merupakan paradigma IRM yang sekali lagi bukannya tidak relevan, hanya saja belum cukup. Praksisme Kritis ialah berpijak pada QS Ali Imran ayat 191: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”. Mengisaratkan bahwa IPM dalam melakukan tindakan transformative (aksi nyata) merupakan manifestasi dari proses atau usaha berfikir-reflektif perpaduan fikr dan dzikr.
Kemudian Ada ayat al-Quran yang bisa dijadikan sebagai pijakan atau paradigma IPM atas problematika diatas merupakan data empiris yang menggambarkan realitas. (QS, Ali Imron :110) “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. Ayat diatas harus memacu semangat IPM, kedepan harus aharus terlibat aktif pada persoalan-persolan riil dikalangan pelajar, sebagai the choosen organization (gerakan elite) yaitu organisasi terpilih, organisasi terbaik baik dan popular untuk pelajar, yang terdiri dari komunitas pelajar yang menyuruh yang ma’ruf (humanisasi), mencegah dari yang mungkar (liberasi).
Kesatuan Paradigma: Kritis Terbuka, Keilmuan, dan Hati Suci
Konsep cara pandang atau paradigma tentang kesempurnaan budi yang lahir karena mengerti baik-buruk, benar-salah, dan kebagagiaan-kesengsaraan. Paradigma tersebut dapat dicapai jika dengan akal yang sempurna. Yaitu, 1). kritis-terbuka yaitu mengunakan akal-kritis dan kreatif-bebas yang diperoleh dari belajar (2). Keilmuan, arti ilmu disini adalah inti ajaran Islam dengan satu Asas kebenaran yang memandang bahwa semua manusia berkedudukan sama. (3). Hati-Suci, artinya kebenaran hanyalah satu, sesuai dengam hati dan akal-pikiran yang suci dan berfungsi bagi kebahagiaan dan kegembiraan sebagian besar manusia.
1). Paradigma Kritis-Terbuka
Kehebatan dan kebaikan sebuah organisasi atau gerakan ialah jika ia memiliki sikap terbuka menerima ilmu, pendapat, kritik, yang berbeda dari luar kemudian menghasilkan konsep kritis dan aksi-transformatif kepada masyarakat atau lingkungan sosialnya. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (criticl cnsciosess). Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan sistim pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut. 33
Pertama kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistim politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses belajar mengajar tersebut dalam prepektif Freirean di sebut sebagai pendidikan fatalistik. Proses pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistim dan struktur terhadap satu permalahan masyarakat. Murid secara dogmatik menerima ‘kebenaran’ dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami ‘makna’ ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.
kedua adalah kesadaran naif. Keadaan yang dikatagorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat ‘aspek manusia’ menjadi akar penyebab masalah masarakat. Dalam kesadaran ini ‘masalah etika, kreativitas, ‘need for achevement’ dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘salah’ masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atau tidak memiliki budaya ‘membangunan’ dan seterusnya. Oleh karena itu ‘man power devlopment’ adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam kontek ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada sudah baik dan benar, merupakan faktor ‘given’ dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistim yang sudah benar tersebut.
Ketiga disebut sebagai kesadaran Kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari ‘blaming the victims’ dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih murid untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidak adilan’ dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya.
Selanjutnya, Paradigma Kritis-Terbuka ini beransumsi bahwa untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. IPM meskipun sebagai organisasi otonom dan independen dalam dunia dakwah dikalangan pelajar tidaklah mengklaim bahwa dirinya sendiri, merasa dapat menyelesaikan persoalan sendiri, tidak memerlukan bantuan dan sumbangan pemikiran dari pihak eksternal dan berujung pada fanatisme komunitas. Oleh sebab itu sikap kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling keterhubungan akan sangat membantu IPM untuk memahami kompleksitas kehidupan yang dijalani dan memecahkan persoalan yang dihadapi dan didukung dengan sikap kritis. {Pertemuan, pertentanga, kritik, perpaduan, penyempurnaan konsep, kompromi dan dialog antar barbagai kelompok, merupakan lahan subur bagi penyusunan sistematika gerakan dakwah IPM.
Paradigma kritis terbuka Ialah pola piker yang tidak rigid, kaku, dan tidak mengenal kompromi karena ada fanatisme. IPM tidak menghendaki fanatisme, yang menimbulkan pola pikir yang menyerang pola piker dan pemahaman bahkan keimanan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga sulit diajak bertukar pikiran secara jernih dengan kesediaan untuk melakukan proses terbuka (take and give). Paradigma IPM menjadi kacamata landasan berpikir, selalu membuka pikiran yang datang dari luar sekaligus membuka dialog dengan siapapun yang dipandang berbeda dengan pemikirannya, namun dilandasi dengan hati suci yakni aqidah yang kokoh. IPM patut mencohtoh KHA Dahlan yang selain gemar berdiskusi dengan elite dari Boedi Oetomo dan Syarikat Islam yang dirinya terlibat di dalamnya, juga dengan pihak lain yang dianggap berbeda seperti dengan Semaun dan kalangan pendeta. Dalam catatan Jainuri, Kyai Dahlan bahkan pernah menganjurkan agar kajian tentang agama Kristen diadakan di lingkungan masjid-masjid kaum muslimin. Dalam rekam pikiran yang ditulis Kyai Hadjid (edisi baru 2005: 20-21), bahwa Kyai Dahlan pernah menyatakan sebagai berikut:
“Orang yang mencari barang yang hak kebenaran itu perumpamaannya demikian: “Seumpama ada pertemuan antara orang Islam dan orang Kristen, yang beragama Islam membawa Kitab Suci Al-Qur’an dan yang beragama Kristen membawa Kitab Bybel (Perjanjian Lama dan Baru), kemudian kedua kitab suci itu diletakkan di atas meja. Kemudian kedua orang tadi mengosongkan hatinya kembali kosong sebagaimana asal manusia tidak berkeyakinan apapun. Seterusnya bersama-sama mencari kebenaran, mencari tanda bukti yang menunjukkan kebenaran. Demikianlah kalau memang semua itu membutuhkan kebenaran. Akan tetapi sebagian besar dari manusia hanya menurut anggapannya saja, diputuskannya sendiri. Mana kebiasaan yang dimilikinya dianggap benar dan menolak mentah-mentah terhadap lainnya yang bertentangan dengan miliknya.”
Kyai Dahlan sebagaimana dituturkan Kyai Hadjid (lo.cit) dalam pengembangan pemikiran kritisnya itu merujuk pada Al-Quran Surat Luqman (ayat ke-21) tentang sikap taklid mengikuti jejak orang-orang terdahulu, Surat Az-Zumar (ayat ke-17 dan ke-18) tentang sikap kritis ulul-albab, dan pernyataan Muhammad Abduh yang menyatakan: “Kebanyakan manusia, mula-mula sudah mempunyai pendirian, setelah itu baru mencari dalil dan tidak mau mencari dalil selain yang sudah cocok dengan keyakinannya dan jarang sekali mereka mencari dalil untuk dipakai dan diyakinkan”, serta pernyataan “manusia itu benci kepada yang tidak diketahuinya”.
Paradigma kritis-terbuka secara aksiologis hendak manawarkan pandangan dunia (world view) manusia beragama dan berpengetahuan baru yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, jujur dan dapat depertanggungjawabkan secara publik, dan berpandangan kedepan atau berkemajuan.
2). Keilmuan (scientific) / liberasi
Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan dan merupakan titik awal kerisalahan Nabi Muhammad justru tentang “iqra”, yang mengandung pesan sekaligus perintah imperatif kegiatan keilmuan. Islam memerintahkan atau mengajak orang beriman untuk berpikir dan mencari ilmu, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, mengangkat kaum berilmu ke derajat tertinggi. Kegiatan iqra bukan hanya diperintahkan Tuhan baik dalam logika naratif (kisah) dan retorik (nadhar) maupun imperatif (iqra‘), bahkan dengan tegas Allah menyatakan bahwa mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya laksana binatang melata (dawâb) di muka bumi ini (QS Al-Anfal [8]: 22).
Islam hadir menjadi agama yang mencerahkan kehidupan. Agama yang melakukan lintas gerak peradaban ”lituhrijâ al-nâs min al-dhulumât ila al-nûr”, yang membebaskan manusia dari ”kegelapan” (kejahiliyahan) kepada ”cahaya” (kebenaran, al-Islam). Karena tradisi pencerahan (tanwir) itulah maka Islam berhasil menjadi kekuatan dunia di kala Barat kala itu tengah tertidur lelap dalam kegelapan peradaban. Karena itu jika ingin mengukir kejayaan Islam kembali, salah satu pilarnya ialah membangkitkan kembali etos dan tradisi keilmuan disertai pengembangan teknologi yang unggul yang basisnya ialah dasar iman dan moral yang kokoh, yang bersumber pada tauhid sebagai bingkai fundamental dari rancang-bangun peradaban Islam.
Di sinilah pentingnya paradigma keilmuan (scientific) IPM yakni yang memiliki ciri-ciri pelajar yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mendalam ilmunya (QS Ali Imran/3: 7); berfikir sekaligus berdzikir (QS Ali Imran/3: 190-191), mengembangkan nalar kritis (QS Az-Zumar/39: 18), memisahkan al-haq dengan al-bathil atau kebenaran dari kebathilan (QS Al-Maidah/5: 100), menyampaikan ilmu dan mengembangkan hubungan kemanusiaan yang baik dengan sesama (QS Ar-Ra’du/13: 22), bertaqwa kepada Allah dengan iman dan ilmunya (QS Albaqarah/2: 197), dan lain-lain.
Paradigma keilmuan IPM terintegrasi dalam kekuatan iman, ilmu, dan amal yang bersifat profetik- transformatif untuk tampil sebagai pembawa misi Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin di zaman modern abad ke-21 ini. IPM yang memiliki basis pelajar memiliki tanggungjawab penting bagaimana berada di barisan depan dalam mengusung gerakan keilmuan dalam membangun masa depan Islam dan umat Islam saat iniSemua manusia harus belajar dan menjadi guru dalam madrasah, sekolah, pesantren atau di lapangan, pasar, penjara, dan di jalan-jalan. Meraka yang tinggi ilmunya (ulama) atau sedikit wajib menyebarluaskan ilmu (pengetahuan) yang dimiliki. Penyebarluasan ilmu dilakukan dengan doktrin “jadilah guru sekaligus murid”. 143 Mustahil seseorang akan memperoleh ilmu kecuali melalui pendidikan dan pengajaran yang dijalankan yang dijalankan oleh guru. (142). Karena itu, pendidikan harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan akalnya tersebut, yaitu yang mendidik akal tentang kesesuaian pikiran dengan kenyataan.
Pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang berguna (pragmatis), bisa dikerjakan dan sesuai fakta (keadaan) atau kontekstual. Sementara kegunaan pengetahuan adalah jika bisa memperbaiki tindakan manusia yang buruk dan yang salah. Kemampuan memilih yang salah dan benar, baik, dan buruk, dan kemampuan memecahkan masalah harus didasari fakta yang benar dengan belas-kasih sebagai dasar keutamaan.Pendidikan dan pengajaran yang berguna bagi akal-pikiran jauh lebih penting disbanding memenuhi kebutuhan makan. 143 Kemudian pendidikan agama harus didasari pengakuan atas hak dan kebenaran akal dan ilmu, mengakui keinginan dan nafsu manusia, dan dibuktikan dengan jalan ilmu dan akal-pikiran. Oleh karena itu ilmu harus ditujukan untuk menghidupkan akal pikiran dan dikembangkan menjadi kecintaan terhadap sesame manusia dan pembebasan manusia dari penderitaan (liberasi).
Selain itu paradigm keilmuan IPM harus mampu memperbaiki taraf hidup, kebebasan berkreasi, kebaikan moral, dan bertanggung jawab atas kebaikan hidup pelajar (pencari ilmu) itu sendiri, masyarakat, dan dunia kemanusiaan, serta tauhid (transendensi). Kemudian paradigm keilmuan yang dibangun ialah yang mampu menyatukan (integrasi) antara kebudayaan dan Agama, selain kesatuan manusia termasuk dengan beda Agama bagi kepentingan hidup ummat.
Sehingga keilmuan yang dibagun oleh IPM dalam bahasa Kuntowijoyo ialah integralisasi dan objektifikasi. Ilmu tidak ada lagi pendekotomian atau pemisahan antara ilmu Barat dan Islam, Sain dengan Agama. Ilmu adalah untuk semua, tidak hanya untuk orang Islam sendiri tetapi juga untuk ummat yang lain karena Islam ialah rahmatan lil Alamin. IPM pada hakikatnya adalah gerakan elite atau gerakan pelajar yang identik dengan keilmuannya. Namun, IPM juga memiliki peran social sebagai bentuk kerahmatan bagi seluruh ummat manusia. Tidak hanya untuk peryarikatan, ummat, dan bangsa, tetapi juga kader kemanusiaan.
Sekali lagi bahwa tidak ada perbedaan atau pertentangan antara ilmu, daya kreatif akal, dengan tauhid. Atau bahasa lain IPTEK dengan Tafsir al-Qur’an. Perbedaan antara keduanya akan terjadi manakala keduanya mengalami kesalahan. Kebenaran IPTEK dan tafsir ayat dilihat dari fungsi pragmatisnya begi perbaikan atau kemaslahatan kehidupan dan kebahagiaan bagi seluru ummat manusia karena keduanya merupakan kesatuan sejarah dalam pegalama intelatual. 146
3). Hati Suci
Kebahagiaan manusia di dunia bisa diperoleh jika seluruh manusia bersatu atas dasar kebenaran yang satu.
Kemudian hati-suci akan menghasilkan akal-pikiran-suci. Sedangkan akal-pikiran-suci adalah akal yang sehat dan kesehatan akal bisa dicapai jika terus menerus diberi pengetahuan melalui pendidikan akal dengan ilmu logika.
Kesempurnaan Akal-Pikiran akan diperoleh seseorang apabila bias membedakan dan membandingkan kebenaran dan kesalahan, kebaikan dari keburukan dan yang tidak merusak hati-suci dan mendatangkan kesusahan dan penderitaan. 142.
Sebagaimana KHA Dahlan dengan tegas meletakkan akal suci akar bagi metodologi memahami, menafsirkan, dan mewujudkan nilai-nilai islam dalam kehidupan empiric. 145. Akal suci artinya akal yang dibimbing dengan hati suci ini sebagai alat untuk melakukan transformasi social dalam kehidupan masyarakat atau realitas. Sehingga wahyu al-Qur’an akan selalu shalih likulli zaman wa makan. Inilah yang dimaksud dengan Islam berkemajuan, yakni Islam yang sesuai dengan semangat zaman, bahkan melampaui zamannya.
Aksi kebudayaan dan transformasi social adalah bentuk dari perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Inilah yang dinamakan modernisasi. Islam tidak perlu dipertantangkan dengan modernisasi, namun modernisasi (akal) dijadikan alat untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat dengan cara diintegrasikan dengan Tauhid (tansendensi) yang disebut dengan akal suci inilah yang mampu membagun peradaban utama kehidupan ummat manusia. Dengan akal dan daya kreatif manusia untuk mengelola alam semesta ini sebagai bentuk manifestasi khalifah adalah merupakan bukti keyakinan tauhid (iman).






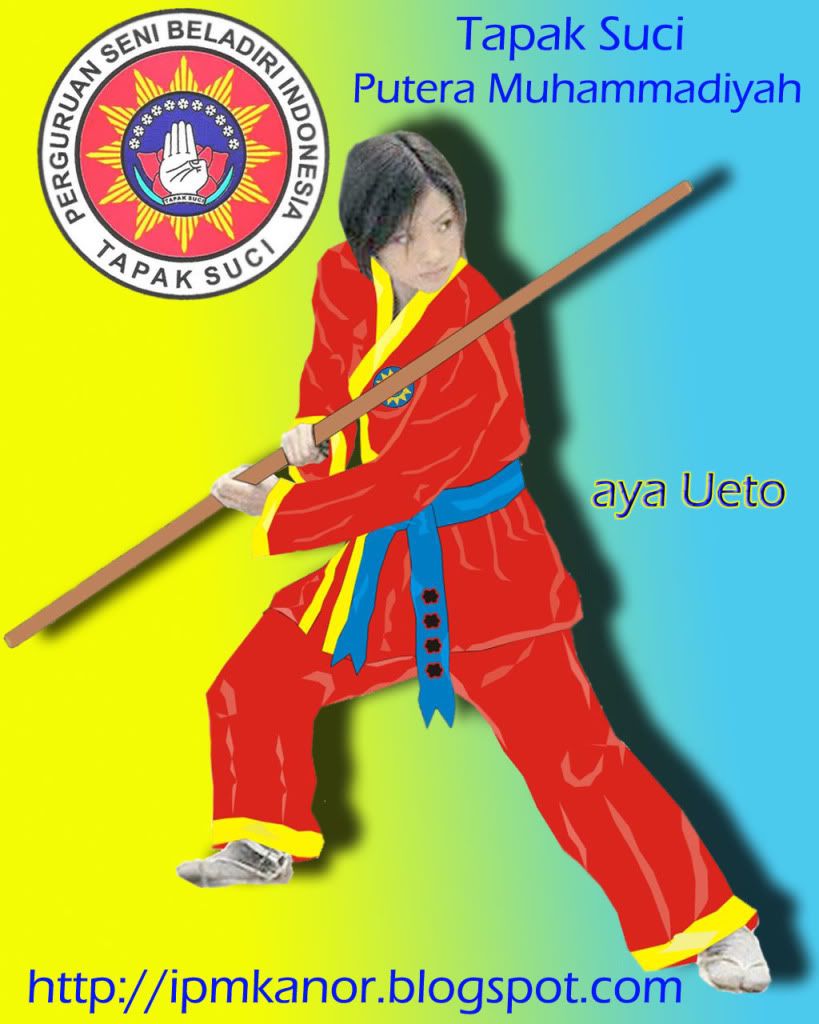

0 Diskusi:
Posting Komentar